Sebelas tahun lalu, tepat aku melakukan perjalanan ke pedalaman Baduy. Tiba-tiba saja malam ini aku kangen mengenang betapa subtilnya pengalaman rohani yang aku dapati. Sore tadi aku terlibat pembicaraan santai yang serius bersama Ragil seorang sarjana Filsafat UGM yang kini tengah asyik dengan kafe Philokopie buatannya di Jakal km 5.5. Obrolan ringan di kafe itu tak terasa tiga jam lamanya hingga aku tak terasa menghabiskan dua cangkir ground kopi Toraja. Ragil yang alumni MAN Wonosobo tempat dimana dulu pernah aku mengabdi menjadi guru tengah diserang badai 'serotonin' atas apa yang akhir-akhir ini sedang dialami dalam hidupnya. Empat tahun lebih belajar filsafat di UGM rasanya menjadi nadir ketika sebuah peristiwa kecil mengaduk-aduk ruang simulakra di kepalanya. Itu adalah sebuah peristiwa sederhana. Tetapi tak cukup satu rak buku filsafat mampu menjelaskan apa yang sebenarnya tengah terjadi.
Ya,... perisitiwa sederhana yang kadang menjadi titik balik kehidupan seseorang. Seperti sederhananya perjalananku ke pedalaman Baduy tahun 2002 lalu dan berdampak besar pada kehidupanku sampai saat ini. Tak mudah aku menuliskannya apa yang kurasakan saat itu di blog yang terbatas ini. Harus menyalin ulang buku harian yang kutulis waktu itu. Untunglah ketika browsing-browsing menemukan tulisan ini yang ketika kubaca nyaris serupa dengan pengalaman yang aku alami ketika pertama menginjakkan kaki di Baduy. Padahal tulisan di bawah ini kisahnya terjadi 54 tahun lalu! hm....
Kata kunci yang ada dalam kepalaku saat masuk ke kamarnya mbah Google adalah perjalanan ziarah ke Badui. Dan yang kudapat adalah artikel ini berjudul : Baduy – Sebuah Perjalanan Batin Ke Suku Kuno tahun 1959. Sebuah kontemplasi yang serupa kurasa. Bahkan artikel ini ditulis Pebruari 2010 (kini aku menulis Pebruari 2013) dan perjalanan aslinya terjadi Januari 1959 (sementara perjalananku Januari 2002). Ragil pasti akan tertawa seraya berkata tidak percaya dengan yang namanya 'kebetulan', 'sign' atau apalah... bagiku ini adalah sebuah COSMIC CONSCIOUS....
__________________________________________________________
Baduy – Sebuah Perjalanan Batin Ke Suku Kuno tahun 1959 (http://artshangkala.wordpress.com)
Oleh : Suria Saputra.
Keterangan :

Sebelum berangkat, kami cari dulu keterangan tentang tempat dan orang yang akan kami kunjungi dengan memajukan pertanyaan‑ pertanyaan kepada orang‑orang yang pernah pergi berziarah ke Baduy. Mereka kebanyakan adalah petani‑petani dan pedagang‑pedagang yang ingin maju dalam masing‑masing perusahaannya. Dan ada pula yang datang di Baduy untuk minta obat bagi keluarganya yang sakit, karena obat dokter tak dapat menolongnya. Maksud kedatangan mereka itu sepanjang katanya, ada yang berhasil, ada yang tidak.
Mereka yang datang ke sana dengan sesuatu maksud untuk memperbaiki nasibnya, sepanjang katanya tidak boleh bermalam disana, setelah mendapat jawaban yang diinginkannya, waktu itu juga ia harus berangkat pulang, tidak boleh menoleh ke belakang.
Setelah keterangan‑keterangan dikira cukup untuk bekal pertemuan pertama kami peroleh, barulah kami berangkat, ialah: Saya sendiri, Pak Atmawidjaja ‑ Kepala Sekolah Rakyat di kota Bogor, dan seorang wanita Ibu Arum Suwita. Ibu Arum ini adalah seorang wanita yang kuat berjalan kaki dan banyak pengalamannya, jauh perjalanannya. Demak, Madura, Tengger, Kalimantan, Ngampel dan tempat-tempat yang beriwayat lainnya telah dikunjunginya. Dan telah berkali-kali pula Ibu Arum ini pergi ke Baduy. (Untuk melanjutkan klik permalink)
Jam 06.00 pagi pada waktu yang tersebut di atas tadi, kami dari kota Bogor menuju ke barat, berkendaraan bus, melalui Jasinga, Cipanas dan berhenti di Haurgajrug jam 09.30 pagi hari. Dari sini berjalan kaki menuju ke kampung Karang untuk singgah dan bermalam di sana.
Tiba di Karang jam 06.30 petang hari. Waktu itu di Karang sedang diadakan perayaan khitanan yang cara-caranya berbeda dengan di tempat lain, hampir sama dengan cara khitanan di Baduy.
Kampung Karang adalah sebuah kampung yang penghuninya hampir seperti Baduy. Kepala kelompoknya pun disebut Puun. Ketika itu, kami tak sempat berkenalan dengan Puunnya, karena esok harinya pagi-pagi harus berangkat lagi. Baru dapat berkenalan dengan orang-orang tua di sana setelah pulang dari Baduy.
Di Karang, rombongan kami bertambah dengan dua orang suami-istri. Laki-lakinya bernama Sopian, orang Jakarta dan istrinya orang Karangcombong. Sedang perjalanan kami hari itu akan menuju Karangcombong, untuk singgah dan bermalam di sana.
Di dalam hutan lebat yang pernah kami masuki itu, saya menginginkan udara yang sejuk, pendengaran yang sunyi, pemandangan yang menghijau disertai air bening yang mengalir.
Penduduk Karangcombong ini menurut tilikan kami pada waktu itu, adalah orang baik-baik. Agama Islam tampak ditaati dengan bukti adanya mesjid dan madrasah. Dalam prakteknya agama Islam itu berasosiasi dengan agama lama, ternyata dari mantera-manteranya.
Sungguh tak kami sangka bahwa dua tahun kemudian penduduk kampung inilah yang mengganas merusak hutan-hutan larangan Baduy, yang keadaannya bersifat “Hutan Pelindung Mutlak”. Rusaknya hutan ini berarti rusaknya tempat-tempat yang ada di aliran sungai sebelah bawah, yang hulunya di hutan larangan itu. Kemudian hari ternyata, bahwa keganasan orang Karangcombong terhadap hutan larangan / Hutan Pelindung Mutlak itu disebabkan setelah di kampungnya ada seorang haji berasal dari Leuwidamar. Haji inilah yang menjadi kepala dan penganjur rakyat di sana agar supaya berladang di hutan larangan. Malam harinya, di kampung ini kami tak dapat melepaskan lelah, karena dikerumuni oleh orang-orang tua di tempat itu. Mereka bertanyakan bermacam-macam soal yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa di kota dan di negara.
Kedatangan kami di kampung ini mendapat sambutan dan jamuan yang istimewa, meskipun mereka tidak diberi tahu lebih dahulu.
Tempat dimana kami berjumpa, ialah sebuah bangunan yang kami sebut “dangau-dangau”. Untuk disebut gubug, terlalu besar dan lengkap. Dangau-dangau ini hampir sebesar rumah mereka. Pada waktu berhuma, kebanyakan orang Tangtu diam dan bermalam di dangau-dangau ini.
Kami dapati Puun Manten sedang memintal tali untuk menjalin lanjak (jaring perburuan). Mula-mula orang ini kelihatan acuh tak acuh kepada kedatangan kami, karena sedang asyik bekerja. Kemudian setelah ia mengemasi pekerjaannya, kami didekatinya dan berkatalah ia: “Teu harti aing, naeun karah rea jelema datang ka dieu”.
Susunan kalimat ini sudah berlainan dengan bahasa Sunda biasa. Awalan dan ahiran tak terlalu dihiraukan. Arti kalimat itu: “Aku tak mengerti mengapa banyak orang datang kemari”.
Setelah kami berkenalan dengan tak berjabatan tangan, Puun Manten berusaha berbicara dengan bahasa Sunda Halus. Akan tetapi saya minta kepadanya, agar percakapan dilakukan dengan bahasa Sunda mereka. Hal-hal yang tak dapat saya pahamkan, saya minta penjelasan kepadanya.
Dengan kalimatnya yang tegas dan jelas, acapkali dipatahkannya perkataan lawan bicaranya, hingga sukar dielakkan.
Pada hemat saya tampan orang ini tidak pernah gentar walau berhadapan dengan siapa jua pun. Dugaan saya tentang sifat orang ini yang didapat dari kesimpulan jawaban orang-orang yang telah pernah pergi ke Baduy (di atas telah dikemukakan), adalah orang yang tak menyukai manusia yang berjiwa peminta-minta. Disangkanya semua orang sebagai dirinya, ialah dapat menyelesaikan sendiri segala keperluan hidupnya.
Oleh karena itu, saya amat berhati-hati menjawab pertanyaannya, seolah-olah sedang berhadapan dengan seorang penguji. Pada hemat saya, andai kata waktu itu lidah saya terpeleset, niscaya kami tak diizinkan bermalam di rumahnya. Istimewa pula kalau kami minta apa-apa sebagaimana keterangan yang kami peroleh, tentunya disuruh pulang pada waktu itu juga. Sedang kami perlu mengetahui keadaan rumah bersama alat-alatnya yang ada di daerah Baduy Dalam itu. Bahkan pada persangkaan saya waktu itu, niscaya Puun Kais itu karena bekas pemimpin, berumah bagus, dengan alat rumah tangganya yang mewah.
Pertanyaan ini adalah diluar dugaan kami, hingga saya tertegun dan meraba-raba jawaban yang akan dikemukakan.
Saya terdesak, tak dapat mengelakkan kalimat-kalimat Puun Kais yang
berlogika, mendesak dan bersifat mematahkan itu. Oleh karena itu, saya
berbicara lebih berhati-hati lagi, karena ternyata orang yang saya
hadapi ini tak dapat dibawa lemah. Agaknya orang-orang yang lemah di
dalam hatinya, ditertawakan.
Puun Kais tersenyum melihat saya kemalu-maluan itu.
Selanjutnya bertanya pula.
Puun Kais diam sejenak, agaknya sedang berpikir. Sambil tersenyum, berkatalah pula:
Pada waktu itu kami tinggal berempat. Orang Karang Jombong dua-duanya
disuruh pulang oleh Puun Kais. Sedang Sopian, orang yang ikut dari
Karang itu, masih terus bersama-sama kami. Ia agaknya berlawanan dengan
maksud kami, karena sementara berbaring berkata bahwa tanah Baduy
sungguh baik untuk dijadikan sawah. Ia tak tahu bahwa tanah pegunungan
yang bentuknya demikian dan menjadi hulu beratus-ratus anak sungai,
kalau dijadikan sawah, akan berakibat erosi besar-besaran. Disangkanya,
bahwa kedatangan kami kesana itu akan dapat menolong untuk menyampaikan
cita-citanya. Maka adalah selayaknya Puun Kais menyindir-nyindir kami
akan membuat sawah. Agaknya Puun Kais telah mendapat firasat yang tidak
baik, karena ternyata Sopian ini kelak kemudian hari ikut menjadi
perusak hutan. Sopian waktu itu memakai rantai arloji emas dengan mainan
(gantungan) batu merah sebesar ibu jari kaki, yang diikat dengan emas
pula.
Maka batu bersama arlojinya diberikan Sopian kepada Puun Kais.
Setelah batu merahnya itu diamat-amatinya, dikembalikan lagi kepada
Sopian, seraya berkata :
Saya mengambil rokok dan berkata :
Puun Kais memperhatikan pemantik api bensin yang saya pergunakan.
Kalimat ini saya terima sebagai sindiran, karena orang-orang yang
biasa berziarah kepadanya, tentu membawa pemantik api bensin yang tak
asing lagi bagi Puun Kais.
Tengah kami bercakap-cakap, tiba-tiba berdiri seorang Baduy Dalam lain di samping Puun Kais, tak ketahuan darimana datangnya, karena sangat gesitnya bertindak. Ia berkata kepada Puun Kais, bahwa di hutan yang dekat dari sana, ada seekor kancil. Puun Kais menoleh, dan berkata:
Mendengar peristiwa itu, Sopian kawan kami itu berkata:
Puun Kais berkata.
Senja hari, setelah kami mandi di sungai Ciujung, kami diajak
bermalam di rumah Puun Kais yang ada di perkampungan Baduy Dalam
Cikeusik. Kami masih sempat memperhatikan keadaan perkampungan itu.
Rumah-rumahnya sangat berdekatan. Antara rumah dengan rumah tak
berpagar, demikian pula perkampungannya. Rumah mereka bertiang kayu
beratap rumbia. Lantainya dibuat dari bambu yang diremukkan membujur (palupuh = Sunda). Tinggi kolongnya +
1,50 m. Untuk naik ke atas lantai, ada tangga pendek dari bambu. Di
ujung tangga disediakan perian yang berisi air untuk membasuh kaki.
Dapurnya ada di dalam rumah.
Nasinya putih bersih, tetapi keras dan berderai (bear = Sunda), hingga sukar disuapkan. Akan tetapi bagi mereka sudah biasa dan suapnya pun berlainan, ialah nasi itu tak ditaruh diujung jari, melainkan ada di antara telapak tangan dari jari, lalu dilemparkan ke dalam mulutnya. Karena itu ujung jarinya tak sampai masuk ke dalam mulut.
Selesai makan, kami duduk-duduk di atas tikar. Sedangkan Puun Manten
bersama istrinya dan anak-anaknya duduk di atas lantai bambu tak
beralaskan apa-apa. Saya berkata :
Saya mengambil kain putih dari dalam tas dan diserahkan kepada Puun Manten sebagai buah tangan bagi keluarganya.
Kemudian pembicaraan kami beralih kepada peristiwa negara pada masa itu.
Puun Manten bertanya pula :
[1] Ketika buku ini ditulis, kedua-duanya masih hidup dan ada di Bogor.
Ya,... perisitiwa sederhana yang kadang menjadi titik balik kehidupan seseorang. Seperti sederhananya perjalananku ke pedalaman Baduy tahun 2002 lalu dan berdampak besar pada kehidupanku sampai saat ini. Tak mudah aku menuliskannya apa yang kurasakan saat itu di blog yang terbatas ini. Harus menyalin ulang buku harian yang kutulis waktu itu. Untunglah ketika browsing-browsing menemukan tulisan ini yang ketika kubaca nyaris serupa dengan pengalaman yang aku alami ketika pertama menginjakkan kaki di Baduy. Padahal tulisan di bawah ini kisahnya terjadi 54 tahun lalu! hm....
Kata kunci yang ada dalam kepalaku saat masuk ke kamarnya mbah Google adalah perjalanan ziarah ke Badui. Dan yang kudapat adalah artikel ini berjudul : Baduy – Sebuah Perjalanan Batin Ke Suku Kuno tahun 1959. Sebuah kontemplasi yang serupa kurasa. Bahkan artikel ini ditulis Pebruari 2010 (kini aku menulis Pebruari 2013) dan perjalanan aslinya terjadi Januari 1959 (sementara perjalananku Januari 2002). Ragil pasti akan tertawa seraya berkata tidak percaya dengan yang namanya 'kebetulan', 'sign' atau apalah... bagiku ini adalah sebuah COSMIC CONSCIOUS....
__________________________________________________________
Baduy – Sebuah Perjalanan Batin Ke Suku Kuno tahun 1959 (http://artshangkala.wordpress.com)
Oleh : Suria Saputra.
Keterangan :
- Ini merupakan cuplikan dari buku yang berjudul BADUY tahun 1959 oleh Suria Saputra, yang merupakan hasil perjalanannya ke Suku Kuno Baduy (Kanekes). Buku ini terdapat dalam Perpustakaan Prof. Dr. Doddy A. Tisna Amidjaja (yang telah disalin kembali dalam bentuk EYD oleh para pengurusnya di tahun 1995).
- Foto-foto di sini adalah hasil foto sesepuh Sunda, yaitu Ali Sastramidjaja. Dalam perjalanan lahir batinnya di tempat yang sama, Kanekes (Baduy) di tahun 1979.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * *
BADUY

Baduy Luar
Pada 5 hari bulan April 1950, cita‑cita saya untuk pergi ke Baduy baru dapat dilaksanakan.Sebelum berangkat, kami cari dulu keterangan tentang tempat dan orang yang akan kami kunjungi dengan memajukan pertanyaan‑ pertanyaan kepada orang‑orang yang pernah pergi berziarah ke Baduy. Mereka kebanyakan adalah petani‑petani dan pedagang‑pedagang yang ingin maju dalam masing‑masing perusahaannya. Dan ada pula yang datang di Baduy untuk minta obat bagi keluarganya yang sakit, karena obat dokter tak dapat menolongnya. Maksud kedatangan mereka itu sepanjang katanya, ada yang berhasil, ada yang tidak.
Mereka yang datang ke sana dengan sesuatu maksud untuk memperbaiki nasibnya, sepanjang katanya tidak boleh bermalam disana, setelah mendapat jawaban yang diinginkannya, waktu itu juga ia harus berangkat pulang, tidak boleh menoleh ke belakang.
Setelah keterangan‑keterangan dikira cukup untuk bekal pertemuan pertama kami peroleh, barulah kami berangkat, ialah: Saya sendiri, Pak Atmawidjaja ‑ Kepala Sekolah Rakyat di kota Bogor, dan seorang wanita Ibu Arum Suwita. Ibu Arum ini adalah seorang wanita yang kuat berjalan kaki dan banyak pengalamannya, jauh perjalanannya. Demak, Madura, Tengger, Kalimantan, Ngampel dan tempat-tempat yang beriwayat lainnya telah dikunjunginya. Dan telah berkali-kali pula Ibu Arum ini pergi ke Baduy. (Untuk melanjutkan klik permalink)
*
Jam 06.00 pagi pada waktu yang tersebut di atas tadi, kami dari kota Bogor menuju ke barat, berkendaraan bus, melalui Jasinga, Cipanas dan berhenti di Haurgajrug jam 09.30 pagi hari. Dari sini berjalan kaki menuju ke kampung Karang untuk singgah dan bermalam di sana.
Tiba di Karang jam 06.30 petang hari. Waktu itu di Karang sedang diadakan perayaan khitanan yang cara-caranya berbeda dengan di tempat lain, hampir sama dengan cara khitanan di Baduy.
Kampung Karang adalah sebuah kampung yang penghuninya hampir seperti Baduy. Kepala kelompoknya pun disebut Puun. Ketika itu, kami tak sempat berkenalan dengan Puunnya, karena esok harinya pagi-pagi harus berangkat lagi. Baru dapat berkenalan dengan orang-orang tua di sana setelah pulang dari Baduy.
Di Karang, rombongan kami bertambah dengan dua orang suami-istri. Laki-lakinya bernama Sopian, orang Jakarta dan istrinya orang Karangcombong. Sedang perjalanan kami hari itu akan menuju Karangcombong, untuk singgah dan bermalam di sana.
*
Perjalanan Haurgajrug – Karang dan Karang – Karangcombong melelahkan
dan meletihkan, karena turun naik gunung, tapi tak seperti yang saya
cita-citakan. Cita-cita saya sebelum berangkat, untuk pergi ke Baduy
itu, tentu melalui jalan yang berhutan lebat, sebagaimana hutan-hutan
yang pernah kami masuki dalam tiap-tiap tahun atau setahun dua kali,
manakala ada kesempatan.Di dalam hutan lebat yang pernah kami masuki itu, saya menginginkan udara yang sejuk, pendengaran yang sunyi, pemandangan yang menghijau disertai air bening yang mengalir.
*
Rombongan kami tiba di kampung Karangcombong jam 05.30 petang hari.
Jadi antara Karang dan Karangcombong kami jalani hampir satu hari penuh,
karena berangkat dari Karang jam 07.00 pagi-pagi.Penduduk Karangcombong ini menurut tilikan kami pada waktu itu, adalah orang baik-baik. Agama Islam tampak ditaati dengan bukti adanya mesjid dan madrasah. Dalam prakteknya agama Islam itu berasosiasi dengan agama lama, ternyata dari mantera-manteranya.
Sungguh tak kami sangka bahwa dua tahun kemudian penduduk kampung inilah yang mengganas merusak hutan-hutan larangan Baduy, yang keadaannya bersifat “Hutan Pelindung Mutlak”. Rusaknya hutan ini berarti rusaknya tempat-tempat yang ada di aliran sungai sebelah bawah, yang hulunya di hutan larangan itu. Kemudian hari ternyata, bahwa keganasan orang Karangcombong terhadap hutan larangan / Hutan Pelindung Mutlak itu disebabkan setelah di kampungnya ada seorang haji berasal dari Leuwidamar. Haji inilah yang menjadi kepala dan penganjur rakyat di sana agar supaya berladang di hutan larangan. Malam harinya, di kampung ini kami tak dapat melepaskan lelah, karena dikerumuni oleh orang-orang tua di tempat itu. Mereka bertanyakan bermacam-macam soal yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa di kota dan di negara.
*
Pada hemat kami, bagi seseorang pegawai Jawatan Penerangan, saat dan
keadaan sedemikian itulah yang merupakan peristiwa yang sebaik-baiknya
untuk meresapkan keinginan-keinginan pemerintah kepada rakyat. Di tempat
dan waktu yang seperti itu, bukannya kita yang ingin berpidato,
melainkan mereka yang ingin mendapat nasihat.Kedatangan kami di kampung ini mendapat sambutan dan jamuan yang istimewa, meskipun mereka tidak diberi tahu lebih dahulu.
*
Keesokan harinya, ialah pada 6 hari bulan Januari 1959, jam 7
pagi-pagi, kami berangkat menuju daerah Baduy Dalam Cikeusik (Tangtu
Padaageung). Rombongan kami berkurang dengan seorang, ialah wanita istri
Sopian, tapi bertambah dengan 2 orang laki-laki ialah penghuni rumah
tempat kami bermalam dan seorang iparnya; jadi berjumlah 6 orang, 5
orang laki-laki dan seorang wanita.
*
Perjalanan yang turun naik di lereng gunung, hingga adakalanya lutut
mengenai dagu, sangatlah melelahkan dan meletihkan. Nafas turun naik
dengan cepatnya bagaikan orang berlari cepat. Pakaian basah kuyup dengan
keringat bagaikan habis ditimpa hujan. Walaupun demikian lelah dan
letih itu, bagi saya dapat dilipur oleh keadaan dan suasana hutan yang
saya cita-citakan. Hutan ini bernama Leuweung Kolot (Rimba
Tua); kayu-kayunya besar-besar, bermacam-macam, berdahan rindang berdaun
rimbun, hingga adakalanya sinar matahari tak sampai di bumi karena
terempang oleh daun-daunan yang rimbun itu.
*
Kami pernah masuk hutan Cimari yang letaknya kira-kira 26 km ke
sebelah dalam dari Cikotok, Banten Selatan (tempat tambang emas). Hutan
ini terkenal hutan gelap, karena cahaya matahari terempang oleh
daun-daunan hingga tak menerangi bumi. Tapi keindahannya kalau dibanding
dengan Leuweung Kolot Baduy, masih kurang. Pengantar sukarela kami dari
Karangcombong itu, seorang diantaranya membawa bedil penembak babi.
Katanya untuk menjaga keselamatan dan keamanan kami kalau-kalau di jalan
bertemu dengan binatang buas atau dengan orang-orang pengganggu
perjalanan.
bermusik di ‘dalam’
Kira-kira jam 13.00 tengah hari, kami tiba di perhumaan Cikeusik.
Orang Baduy Dalam yang mula-mula kami jumpai itu adalah Puun Manten.
Kata “manten” ini bahasa Sunda Halus dari kata “pensiun”. Tapi di Baduy
tak ada pensiunan, artinya Puun yang tak menjadi Karolot lagi atau Puun yang sudah berhenti. Beliau bernama Arsadja dan terkenal dengan sebutan Puun Kais.Tempat dimana kami berjumpa, ialah sebuah bangunan yang kami sebut “dangau-dangau”. Untuk disebut gubug, terlalu besar dan lengkap. Dangau-dangau ini hampir sebesar rumah mereka. Pada waktu berhuma, kebanyakan orang Tangtu diam dan bermalam di dangau-dangau ini.
Kami dapati Puun Manten sedang memintal tali untuk menjalin lanjak (jaring perburuan). Mula-mula orang ini kelihatan acuh tak acuh kepada kedatangan kami, karena sedang asyik bekerja. Kemudian setelah ia mengemasi pekerjaannya, kami didekatinya dan berkatalah ia: “Teu harti aing, naeun karah rea jelema datang ka dieu”.
Susunan kalimat ini sudah berlainan dengan bahasa Sunda biasa. Awalan dan ahiran tak terlalu dihiraukan. Arti kalimat itu: “Aku tak mengerti mengapa banyak orang datang kemari”.
Setelah kami berkenalan dengan tak berjabatan tangan, Puun Manten berusaha berbicara dengan bahasa Sunda Halus. Akan tetapi saya minta kepadanya, agar percakapan dilakukan dengan bahasa Sunda mereka. Hal-hal yang tak dapat saya pahamkan, saya minta penjelasan kepadanya.
*
Tanya jawab dengan Puun Manten saya tuliskan di bawah. Akan tetapi
barang siapa yang belum pernah berkata-kata dengan orang Cikeusik,
terutama dengan Puun Kais ini, mungkin menyangka bahwa percakapan kami
ini hanyalah karangan belaka. Untung bagi saya karena Pak Atmawidjaja
dan Ibu Arum menyaksikan pembicaraan kami ini.
*
Orang yang kami hadapi ini, waktu itu berumur 60 tahun, tetapi masih
amat tangkas dan cekatan. Berbadan tegap, senantiasa tegak. Berkulit
kuning agak kemerah-merahan karena cahaya matahari. Matanya bersih,
pandangannya tajam seolah-olah hendak menembus jantung lawannya
berbicara. Rambutnya masih hitam dan panjang, bersanggul, berikat kepala
kain putih mentah. Bajunya kebaya putih, bertangan panjang yang sempit
pergelangannya. Kain sarungnya pun putih pula, hingga di bawah lutut di
atas pertengahan betis, tidak bercelana. Pakaian serba putih itu
kelihatannya kotor, sesungguhnya adalah kain putih mentah yang dicelup
dengan warna kekuning-kuningan. Beliau berbicara fasih. Kalimat
purwakantinya diucapkan dengan sangat lancar, dengan tekanan suara pada
suku kata kedua dari belakang.Dengan kalimatnya yang tegas dan jelas, acapkali dipatahkannya perkataan lawan bicaranya, hingga sukar dielakkan.
Pada hemat saya tampan orang ini tidak pernah gentar walau berhadapan dengan siapa jua pun. Dugaan saya tentang sifat orang ini yang didapat dari kesimpulan jawaban orang-orang yang telah pernah pergi ke Baduy (di atas telah dikemukakan), adalah orang yang tak menyukai manusia yang berjiwa peminta-minta. Disangkanya semua orang sebagai dirinya, ialah dapat menyelesaikan sendiri segala keperluan hidupnya.
Oleh karena itu, saya amat berhati-hati menjawab pertanyaannya, seolah-olah sedang berhadapan dengan seorang penguji. Pada hemat saya, andai kata waktu itu lidah saya terpeleset, niscaya kami tak diizinkan bermalam di rumahnya. Istimewa pula kalau kami minta apa-apa sebagaimana keterangan yang kami peroleh, tentunya disuruh pulang pada waktu itu juga. Sedang kami perlu mengetahui keadaan rumah bersama alat-alatnya yang ada di daerah Baduy Dalam itu. Bahkan pada persangkaan saya waktu itu, niscaya Puun Kais itu karena bekas pemimpin, berumah bagus, dengan alat rumah tangganya yang mewah.
Batok Kelapa sebagai wadah minum air
Kini kami lanjutkan percakapan kami dengan Puun Kais, dalam pertemuan pertama itu.| + | “Saha ieu karah?, Ti mana nya lembur matuh dayeuh maneuh banjar karang pamidangan?” (Siapakah ini?, dimana kampung halamanmu?). |
| - | “Dari Bogor, Girang”. |
| + | “Apakah maksud kalian?” |
| - | “Kami dari Bogor berhasrat untuk bertemu dan berkenalan dengan orang-orang di sini”. |
| + | “Geusan naeun karah?” (untuk apa? atau apakah gunanya?) |
| - | “Begini Girang, bila anak cucuku kelak datang atau tersesat kemari, kalau kami sudah kenal, mudah-mudahan diterima oleh orang sini”. |
| + | “Kalau hanya itu kehendak kalian, sungguh tidak masuk pada akalku (teu harti aing). Kalian datang dari jauh, biayanya pun tidak sedikit. Sungguh tak masuk pada akalku bila hanya untuk menitipkan anak cucumu yang kini tak dibawa. dan ketahuilah, barang siapa yang datang kemari, walau tak dititipkan sekalipun, harus kami sambut dengan cara dan kekuatan kami. Tamu yang lapar kami beri makan, tamu yang mengantuk kami persilahkan tidur. Kami orang Sunda telah mendapat pesan dari nenek moyang kami, katanya: “kelak bila anak cucuku datang kemari, hendaklah dipenuhi barang kehendak dan kekurangannya”. |
Puun Kais tersenyum melihat saya kemalu-maluan itu.
Selanjutnya bertanya pula.
| + | “Apakah maksud kalian yang sesungguhnya, ingin kayakah?” |
| - | “Bukan. Orang kaya pada masa ini risau hatinya, karena banyak harta benda yang dirampok dan dibakar”. |
| + | “Ingin kebal kulit, barangkali?” |
| - | “Tidak. Orang berkulit kebal, biasa dicoba orang. Sekali diparang ia kebal, dua kali tidak luka, tetapi selanjutnya ia akan rebah jua”. |
| + | “Ingin menjadi pemimpin agar dihormat, dipuja orang?” |
| - | “Bukan. Pemimpin yang tak berdarah pemimpin hanya bersifat sementara. Pemimpin yang diangkat oleh orang banyak, akan dijatuhkan oleh orang banyak pula”. |
| + | “Apakah engkau hendak membuat sawah di sini, sebagaimana orang Are (luar Baduy) yang ada di sekitar kami. Ataukah hendak membuat bendungan air, sebagai keinginan Belanda di masa lampau?”. |
| - | “Sekali-kali tidak. Sawah yang terlalu jauh dari tempatku tak berguna bagiku. Dan aku bukannya pegawai pengairan.” |
| + | “Kalau demikian, engkau penyelidik malah”. |
| - | “Bila aku bermaksud berkhianat kepada orang-orang di sini, Girang melihat sendiri. Leherku tak dipalut dengan baja. Sedang golok orang Baduy panjang-panjang dan tajam-tajam. Sekali parang, leherku putus”. |
| + | “Kami orang Sunda, tak diizinkan mencucurkan darah manusia”. |
| + | “Heu-euh (bunyi heu, ditekan dalam-dalam);
Nu bisa ngapung, tunggu turunna. Nu liat kulit, tunggu uduhnya. Nu bisa teuleum, tunggu nyenghapna. Nu ambek, tunggu leuleusna. Aran jelema tetap jelema; daging hipu tulang rangu, ngancik dina kulit bumi. Cara kami, weduk hanteu manggih urut, bedas hanteu ku karana. (Ya… Si pandai terbang, tunggu turunnya, Si kebal kulit, tunggu empuknya. Si pandai selam, tunggu timbulnya. Si pemarah, tunggu lemahnya. Orang adalah orang, berdaging empuk bertulang rapuh; tempatnya di kulit bumi. Cara kami, kebal kulit tak berbekas, kuat tak karena sebab). Dan kini, niscaya kalian merasa lelah. Istirahatlah dahulu. Kalau hendak tidur, tidurlah. Kami di luar. Biasa tidur siang hari, kami tidak. Sementara itu, aku akan menyelesaikan dulu pekerjaanku. Nanti kita teruskan pembicaraan (cacahan) kita” |
*
Kira-kira jam 17.00 petang hari, Puun Kais datang pula kepada kami,
disertai beberapa orang Baduy Dalam lainnya. Puun Kais memperhatikan
batu merah perhiasan Sopian itu seraya katanya:| + | “Aing nyeueung”. (Coba kulihat). |
| + | “Indah benar batu itu. Niscaya pada pendapatmu batu ini keramat. Orang-orang ditempatmu biasa minta keramat kepada batu-batu, kayu atau besi. Bahkan kabarnya ada pula yang minta keramat kepada kuburan. Sungguh bagi kami di sini, cara demikian tak diperkenankan. Kami hanya meminta kepada Yang Satu”. |
| - | “Bolehkah aku merokok?”. |
| + | “Di sini boleh, karena aku tak menjadi Puun lagi. Tapi bila berhadapan dengan Puun Karolot, sekali-kali tak boleh minum rokok”. |
| - | “Mengapa orang Baduy Dalam tak minum rokok?”. |
| + | “Kami buyut (tabu). Tanah disini tak baik untuk tembakau. Jika kami biasa merokok, harus mencari di tempat lain. Sedang perjalanan kami berlainan dengan kamu. Kamu boleh berkendaraan, kami tidak. Bila bepergian, semua tanah yang dilalui haruslah diinjak dan dilangkahi (maksudnya berjalan kaki). Kami tak hendak jadi bujang tembakau”. |
| + | “Bagus benar. Adakah buatanmu sendiri?”. |
| - | “Buatan pabrik, Girang”. |
| + | “Adakah pabrik itu di tempatmu?”. |
| - | “Di luar negeri. Kalau Girang ingin, ambillah”. |
| + | “Aku, tak perlu. Kalau rusak, aku tak dapat membetulkannya”. |
Tengah kami bercakap-cakap, tiba-tiba berdiri seorang Baduy Dalam lain di samping Puun Kais, tak ketahuan darimana datangnya, karena sangat gesitnya bertindak. Ia berkata kepada Puun Kais, bahwa di hutan yang dekat dari sana, ada seekor kancil. Puun Kais menoleh, dan berkata:
| + | “Hari sudah mulai gelap. Kancil itu kita kejar esok hari saja. Jika esok hari tidak ada, biarkan ia hidup”. |
| “Sayang, mengapa tidak dikejar. Kalau kancil itu tertangkap, saya berani menukarinya dengan ikan peda 50 ekor”. |
| + | “Tidak mungkin (hanteu)”. |
| - | “Seratus ekor”. |
| + | “Hanteu”. |
| - | “Dua ratus ekor”. |
| + | “Seribu atau dua ribu ekor pun tetap tidak dapat. Engkau pintar. Ikan peda, banyak di kedai dan di toko. Ia tak ber-nyawa, tak dapat bergerak. Engkau boleh mengambil sesuka hatimu, asal ada uang. Tapi kancil makhluk bernyawa. Dikejar, ia lari, disergap, belum tentu dapat. Andaikata permintaanmu itu kusanggupi, besok atau lusa pedamu sudah ada di sini, sedang kancilku belum tentu ada. Betapa mungkin manusia “tigin ka jangji bela ka lisan” (memenuhi janjinya dan perkataannya). Apabila kancil itu ada di tanganku sekarang atau esok hari, dan engkau ada di depanku, mengapa harus ditukar dengan peda, engkau boleh makan dagingnya sekenyang-kenyangnya”. |
Rumah adat Kanekes / Baduy
Ketika kami tiba, isteri Puun Kais sedang memasak nasi. Puun Kais
sendiri membantu dengan cekatan. Setelah nasi masak, dibentangkannya dua
helai tikar untuk tempat kami makan dan tidur. Penghuni rumah
bersama-sama makan dengan kami. Tempat nasi adalah sebuah piring batu,
besar (piring antik). Kami masing-masing mendapat sehelai daun pisang
untuk pengganti piring, karena mereka tidak boleh mempunyai piring
pinggan biasa. Lauk pauknya lain dari pada ikan peda yang kami bawa dari
rumah, ada garam lama (uyah nahun), gulai atau rebus biji hiris (Cayanus cayan Millsp. fam. Leguminosae), dan petai yang dikeringkan.Nasinya putih bersih, tetapi keras dan berderai (bear = Sunda), hingga sukar disuapkan. Akan tetapi bagi mereka sudah biasa dan suapnya pun berlainan, ialah nasi itu tak ditaruh diujung jari, melainkan ada di antara telapak tangan dari jari, lalu dilemparkan ke dalam mulutnya. Karena itu ujung jarinya tak sampai masuk ke dalam mulut.
*
Tengah kami makan, Puun Mantan berkata.| + | “Agaknya kamu belum biasa makan nasi ladang”. |
| - | “Hanya sukar menyuapkannya saja, ayah. Nasi ayah ini tak dapat dikepal. |
| + | “Sungguh pun begitu, orang yang makan nasi ini lebih tahan lapar dari pada makan nasi di tempatmu. Bila engkau biasa makan nasimu sehari tiga kali, dengan nasi kami ini cukup dua kali saja. Demikian sepanjang kata orang-orang kami yang pernah makan di luar Baduy. Pada hematku nasi sawah itu kurang kekuatannya dari pada nasi ladang”. |
| - | “Mengapa Girang duduk tidak bertikar. Ambillah yang sehelai ini untuk Girang dan Ambu (istri Puun Kais)”. |
| + | “Tidak. Tikar ini kusediakan bagi tamu. Kami tidak biasa bertikar berbantal, apalagi tidur berkasur”. |
| - | “Seorang bekas Puun tidur tidak berkasur berbantal?”. |
| + | “Puun sendiri tidak berkasur berbantal”. |
| - | “Mengapa?” |
| + | “Kami takut kalau-kalau terlalu nyenyak tidur. Terutama bagi kami, tidur di atas kasur itu adalah suatu larangan. Sedang bantal ada juga seorang dua yang empunya. Kamu pun terpaksa di sini tidur tak berbantal, karena aku tak punya barang sebuah pun”. |
| + | “Apakah ini?” |
| - | “Kain putih, Girang”. |
| + | “Ya,… aku tahu ini kain putih. Tapi apakah maksudmu?” |
| - | “Untuk keluarga Girang”. |
| + | “Tidak perlu. Lebih baik kau simpan lagi. Kami orang Sunda hanya boleh memberi tak boleh meminta (wenang mere teu wenang menta). Orang yang pandai meminta adalah tukang baramaen (orang minta-minta)”. |
| - | “Aku sendiri orang Sunda”. |
| + | “Entahlah. Engkau orang Sunda atau bukan tak menjadi soal kepadaku. Bahasamu dapat kupahamkan, tetapi kita berlainan bagian karena berlainan tempat kelahiran. Bagian kami di sini hidup terbatas dengan ketentuan larangan kebuyutan. Bagian kamu di luar, hidup bebas, dapat melakukan sembarang kehendakmu”. |
| - | “Walaupun begitu, kain ini aku yang memberi kepada Girang, bukannya Girang yang meminta kepadaku. Apakah beri-memberi terlarang pula?”. |
| + | “Tidak, bahkan diharuskan. Adakah kainmu ini bukan kau dapat dari pembagian Pemerintah? Kabarnya orang-orang di luar mendapat bagian pakaian dan makanan dari negara (maksudnya distribusi). Tak masuk pada akalku orang yang sehat-sehat seperti kamu sekalian harus dibagi makanan dan pakaian”. |
| - | “Meskipun dibagi, tapi dengan membeli juga. Dan kain putih ini aku tak tahu dengan pasti darimana asalnya, sebab didapat dari istriku”. |
| + | “Walaupun dibeli, harganya tak seperti harga pasar. Dan aku tidak mengerti mengapa engkau membawa benda yang tak kau ketahui asalnya”. |
| - | “Tetapi senang benar hatiku, bila kain putih ini ayah terima. Aku tak sanggup membawanya kembali, karena perjalanan dari sini ke tempatku sangat berat bagiku. Jangankan membawa beban, sedang membawa tubuh pun merasa letih. Lain dari pada itu, andaikata kain ini berasal dari pembagian sekalipun, namun tetap kepunyaanku, bukannya benda curian. Jikalau ayah tak suka memakainya, boleh dibuang, dibakar atau dijual”. |
| + | “Kalau demikian, baiklah kuterima. Tetapi aku berharap agar pemberian ini terbit dari hatimu yang tulus ikhlas, dan hendaklah kau izinkan bila esok atau lusa benda ini kutukarkan dengan benda lain. Kami disini tidak boleh memakai kain sehalus ini. Pakaian kami harus dari kain yang kami tenun sendiri”. |
| + | “Aku mendengar kabar, bahwa negara kita telah terlepas dari kekuasaan Belanda. Masih banyakkah orang-orang Belanda di tempatmu?”. |
| - | Pertanyaan itu tentu saja saya jawab “masih banyak” karena waktu itu adalah tanggal 7 Januari 1950″. |
| + | “Adakah mereka masih menjadi Pangagung? (memegang jabatan tinggi)”. |
| - | “Tidak. Tampuk pimpinan pemerintahan ada di tangan orang-orang awak”. |
| + | “Menurut pakem kami, kekuasaan Belanda di sini harus sudah hapus semenjak 100 tahun yang lampau. Mereka tak mungkin berkuasa kembali, sebab telah tiba “disnya” (batas yang ditunjuk). Setelah habis kekuasaan Belanda, masih ada lagi beberapa bangsa asing yang menduduki tanah air kita ini. Akan tetapi pada hematku, mereka hanya untuk mengacaukan saja, karena kekuasaannya telah dihabiskan Belanda oleh kelebihan waktu 100 tahun itu. Sesungguhnya ada suatu kesalahan besar yang dijalankan oleh orang dulu-dulu di luar. Mereka telah menjual tanah kepada orang-orang Belanda dan orang-orang asing lainnya. Karena itu, orang-orang asing itu mempunyai tanah di sini, bercocok tanam, merasa beruntung dan akibatnya tak mau melepaskan tanahnya itu. Orang-orang Belanda dan orang-orang asing yang datang kemari hanya untuk berdagang dan berjual beli, bukan untuk berkebun berladang. Mereka mempunyai tanah air sendiri”. |
| + | “Kabarnya kamu berperang dengan Belanda”. |
| - | “Terpaksa, karena masing-masing mempertahankan pendiriannya”. |
| + | “Apakah tak lebih baik bila diselesaikan dengan perundingan”. |
| - | “Berunding dan berdamai sudah kami jalankan, tetapi akhir-akhirnya bertempur juga”. |
| + | “Berperang berarti berbunuh-bunuhan. Akibatnya niscaya banyak anak-anak dan perempuan yang terlantar. Pada hematku, bila perundingan itu dijalankan dengan tulus ikhlas, mengapa tak mendapat penyesuaian?. Kamu di luar orang pandai-pandai. Orang-orang Belanda pun tak semua buruk dan tamak; mereka tentu mengetahui bahwa batas kekuasaannya di sini telah lampau. Pada hematku perundingan itu dapat diatur agar tak merugikan kedua belah pihak, misalnya begini: Kepandaian Belanda tentang mengatur negara, membuat uang, membuat pakaian dan sebagainya, kamu ambil dahulu. Orang-orang Belanda yang baik hati, niscaya bersedia memberikan kepandaian itu kepada kamu. Kelak, bila kamu telah pandai sebagai mereka, orang-orang Belanda itu disuruh pulang dengan diberi uang secukupnya untuk tambangan (biaya perjalanan) dan untuk hidup di tanah airnya”. |
| - | “Apakah manusia itu tak boleh berperang?” |
| + | “Kamu boleh, kami tidak. Akan tetapi cara kamu berperang menurut kabar yang kudengar, tak masuk pada akalku. Orang-orang yang berperang pada masa ini, dibolehkan membakar rumah, membunuh perempuan dan anak-anak atau menyiksa orang-orang yang tak berdosa. Pada pakem kami, ada peristiwa perang ayunan. Orang-orang yang berperang ayunan, harus sama senjatanya, seimbang tenaganya. Musuh lawan harus memegang kejujuran. Barang siapa yang tak jujur, meskipun ia menang, tetap kalah”. |
[1] Ketika buku ini ditulis, kedua-duanya masih hidup dan ada di Bogor.





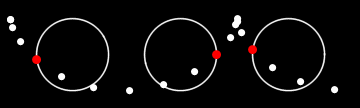



0 komentar:
Post a Comment